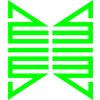Oleh: HASAN ANWAR
DAMPAK nyata reformasi total yang digulirkan sejak empat tahun lalu antara lain terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralistis ke arah sistem yang bersifat desentralistis. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan yang desentralistis, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut, memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, serta prakarsa dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, karakteristik wilayah, dan nilai-nilai sosial-budaya yang berkembang dan berlaku.
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kedudukan kepala daerah adalah semata-mata sebagai “alat” daerah, tidak merangkap “alat” pusat dan tidak merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, tanpa campur tangan pusat. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh presiden. Pengesahan oleh presiden terkait hasil pemilihan oleh DPRD. Hak prerogatif presiden dalam konstruksi ini tidak dianut lagi. Demikian pula Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Ini adalah konsekuensi pemisahan kedudukan yang tegas antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah.
Kesimpulannya, DPRD diberdayakan sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat, sekaligus sebagai pengontrol pemerintah daerah.
Dengan kedudukan DPRD yang kuat vis a vis pemerintah daerah, maka harapan terwujudnya good and clean governance (tata pemerintahan yang baik dan bersih) serta demokratis sesungguhnya sangat besar. Namun, setelah mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, ternyata harapan yang sangat menjanjikan itu berubah menjadi kecemasan di seputar proses otonomisasi tersebut. Di beberapa daerah, otonomi cenderung diartikan secara berlebihan dan kebablasan sehingga mengarah kepada separatisme. Sementara itu, kedudukan DPRD yang begitu kuat telah menimbulkan ekses berupa arogansi di kalangan anggota dewan. Sehingga, DPRD seolah-olah dapat berbuat apa saja, termasuk menetapkan kebijakan yang hanya menguntungksn anggota dewan, tanpa secara jujur dan bertanggung jawab mengadakan perenungan (muhasabah al nafs), sejauh mana dan sebesar apa DPRD telah berbuat dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Bahkan, yang sangat memprihatinkan dan mengecewakan rakyat adalah sinyalemen bahwa banyak wakil rakyat yang terlibat dalam permainan money politics dalam setiap pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) maupun saat proses pambahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah. Sehingga, persoalannya sekarang adalah bukan lagi seberapa jauh fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah dapat benar-benar dijalankan oleh DPRD yang telah diangkat posisinya sedemikian kuatnya, melainkan sejauh mana DPRD telah menjalankan fungsinya dengan benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa berlangsungnya pengendalian sosial bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab di daerah tidak cukup hanya mengandalkan piranti struktural seperti kedudukan DPRD yang kuat, melainkan juga sangat memerlukan piranti yang bersifat kultural. Yakni, kesiapan dan kesadaran semua pihak, baik jajaran pemerintahan maupun legislatif untuk menjunjung tinggi dan menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar demokrasi dan etika religius dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Berangkat dari kenyatan tersebut, maka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar demokrasi meliputi (1) penghormatan terhadap orang per orang sebagai individu (respect of individual of personality) benar-benar ditegakkan. Nilai ini menuntut setiap anggota dewan atau siapa saja yang gandrung terhadap demokratisasi memiliki kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional, seseorang mampu mengendalikan emosinya yang sering tidak terkontrol. (2) Percaya rasionalisasi (ratonality) dalam berdemokrasi. Mengedepankan prinsip rasionalitas setiap mengambil kebijakan, tidak sebaliknya mengumbar emosi yang tak terkendali. (3) Kebebasan individu (individual freedom) dalam berdemokrasi harus memperoleh tempat yang proposional di kalangan warga. Dan, (4) persamaan dalam supremasi hukum, dan semua itu harus tetap dilaksanakan dalam bingkai konstitutionalism.
Dalam rangka mewujudkan good and clean governance, para pemimpin ditantang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etika yang selama ini masih banyak tersembunyi dalam lipatan kitab-kitab suci dan terkesan baru berada pada tataran retorika, pemahaman dan ritual semata, belum menyentuh pada tataran praktis kehidupan, khususnya dalam mengaktualisasikan fungsi mereka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Para aktor, baik yang berada di jajaran eksekutif maupun legislatif, dituntut memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kecerdasan spiritual inilah yang menjadi landasan utama kecerdasan-kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual membuahkan sifat jujur, terpercaya, komunikatif dan transparan.
Penulis adalah staf pengajar IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Sumber: Radar Bojonegoro, Selasa 28 Mei 2002, halaman 22.
Monday, May 5, 2008
Upaya Pengendalian Sosial Pemerintah Daerah Berbasis Etika
Labels:
pemerintahan